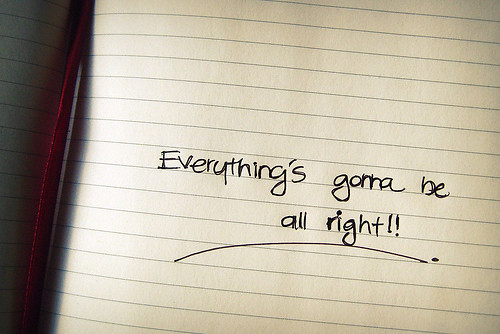Double Esspresso - Temptation
@ DOUBLE ESSPRESSO
Favorites.
Favorites.
Semua orang memiliki hal yang disukai. Tentu saja.
Setiap orang.
Ini lebih dari yang itu.
Aku mudah tertidur beberapa hari ini. Baik, itu artinya baik.
Tanpa mimpi, tanpa Ben, tertidur. Aku masih merasakan sakit dipundakku,
tapi tanpa mimpi, tertidur--itu adalah hal baik.
Dengan kaos hitam, dan celana pendek putih, pilihan warna paling
membosankan, aku duduk disudut @Double Esspresso, menghabiskan satu cup
yoghurt dan menunggu. Hari ini, yoghurt strawberry. Dan espresso
pertamaku.
Dari sudut coffee shop, bukan di coffee bar, seluruh meja kosong
dan kursi yang tersusun rapi, terkesan tersimpan cerita yang ga akan
habis.
Aku membuka halaman halaman website, membalas beberapa email. Perutku terasa lapar, tapi aku membiarkannya.
Hayden datang.
Dia berjalan ke coffee bar. Mencari sarapannya, mencari apapun yang dia butuhkan untuk melengkapi paginya.
Aku jarang berbicara padanya.
Aku membiarkannya, dia membiarkanku.
Tapi pagi ini dia menatapku cukup lama. Bahkan setelah menuangkan espresso, dia berjalan menghampiriku.
'Mau?'
Hayden mengulurkan sandwich.
'Apa isinya?' Tanyaku, dengan mata masih menatap layar laptop.
'Tuna.'
'Ga mau.' Aku menggeleng.
Hayden membuka kotak sandwich, memisahkan Tuna dari sandwich dan mengulurkannya padaku.
'Sekarang, sandwich tanpa Tuna. Makan.'
'Hayden.. sana ah. Lagi serius nih...' Aku menatapnya protes.
Dia kembali mengulurkan sandwich itu padaku.
Namun, kali ini, aku mematuhinya. Melepaskan jari-jariku dari tuts
keyboard. Dan menggigit sandwich. Ekspresiku membuatnya puas. Dia
menggeser kursi didepanku, dan duduk. Memainkan lagu dengan gitarnya.
Beberapa nada, melodi memenuhi coffee shop.
'Kamu berbeda hari ini.'
'New liner.' Aku menjawab pernyataannya.
Dia mengangguk, dan tetap memainkan melodinya. Sepertinya
menuliskan lagu barunya. Dan aku belum bisa menikmatinya, not-nya
sering terhenti, karena Hayden menulskannya di atas komputernya.
Pagi yang menarik.
Aku membiarkan waktu berjalan.
Menyambut tamu yang datang.
Segelas, demi segelas.
Membetulkan poni rambut yang terjatuh.
Mengganti bunga di meja.
Tertawa saat mengobrol singkat dengan tamu.
Aku sendiri, memiliki hal-hal yang kusukai sejak kecil.
Aku pulang kerumah, berlari lari kecil. Rambut panjang, hitam,
tubuh kecil, lincah. Berlari masuk ke rumah, duduk di depan nenek.
Nenek bingung, namun melihat aku serius mengerjakan sesuatu. Nenek
melihat aku duduk, berusaha mengikat sebuah pita mungil di pergelangan
kakiku. Pita merah yang manis.
Nenek saat itu mungkin terenyuh, aku tidak pernah membelikan hadiah untuk cucuku yang satu ini. Begitu mungkin pikirnya.
Nenek berkata, 'Kei, pita itu, kasi ke nenek. Ayo....'
Aku, dengan malu-malu, takut dimarahi. Menolak.
'Nenek, jangan marah... Kei merasa ini cantik...' (karena, mama
tidak suka Keira kecil sembarangan memakai benda-benda sebagai
aksesoris).
'Ga, nenek ga marah... Jangan pakai pita itu, tapi, pita itu bisa
jadi ukuran, ukuran supaya nenek bisa membelikan gelang kaki yang pas
untuk kaki Keira. Keira suka gelang kaki ya? Maaf, nenek tidak pernah
tahu.'
Aku, yang masih kecil. Terharu. Tapi senang.
Sejak itu, aku paling suka Gelang kaki.
Aku tidak keberatan memakai aksesoris lain, tapi setiap kali
merasa ada gelang kaki yang menemaniku berjalan. Suara lonceng kecilnya
yang menemaniku berjalan, hanya mengingatkan aku pada nenek.
Nenek bukan favoritku. Gelang kaki, favoritku.
Aku terlalu jauh dari nenek sejak kecil, sehingga dia tidak pernah menjadi favoritku.
Aku favoritnya.
Itu cuma gelang kaki.
Tapi Ben, tidak hanya Ben.
Tuhan melihat aku, bersama Ben.
Dan ternyata Ia bermaksud mengambilnya. Bukan membelikan aku gelang kaki.
Aku menyentuh gelang kaki, yang dibelikan Ben.
Aku memutuskan mencari gelang kaki baru.
Itu cuma gelang kaki.
Tapi Ben, tidak hanya Ben.
Itu cuma gelang kaki.
Tapi Ben, tidak hanya Ben.
Hatiku berbisik.
Dan seseorang muncul begitu saja dihadapanku. Mengagetkan aku. Lamunanku berakhir.
Sudah terlalu terlambat menikmati sore, sudah hampir malam. Hayden
sudah menghilang entah kemana. Mungkin membereskan gudang untukku, atau
semacamnya. Gitarnya masih disandarkan disamping coffee bar.
'Kamu?'
Dia tersenyum menggodaku. Berdiri didepannya, membuatku merasa menyesal tidak suka minum susu saat kecil.
'Tidak sedang menulis naskah?'
Tanyaku sambil berjalan ke coffee bar, mengeluarkan biji-biji kopi, memisahkannya. Menghitungnya. 42 biji kopi untuk segelas. Aku mengingatkan diriku sendiri.
Dia menggeleng, membuka buku menu. Lalu menatapku bekerja.
'Aku belum tidur, dan harus segera menuli lagi. Ada seminar yang
harus dimulai. Tolong aku, Kei....' Dengan muka memelas dia mencoba
merayuku.
'Ini hari-ku yang indah, jangan rusak hariku. Pesan, dan segera tinggalkan coffee shop ku.'
'Hari-mu sudah hampir berakhir, sudah hampir malam. Haha. Hei Hei, kenapa bersikap memusuhiku, Kei? Ayolah, kita bisa berteman.'
'Berteman? Berhentilah menggodaku, Glass.
Aku menatapnya tak percaya.
'Baik, baik aku mengakui... ' Glass mengangkat tangannya.
Dia lucu, dan aku tidak butuh pria lucu yang menggodaku untuk saat ini.
Favorit, ingat? Aku sedang mengumpulkan semua kesukaanku. Bukan menambahkan satu pria lagi dalam masalahku.
Dan dia menggodaku. Itu tidak adil. Godaan, bukan kesukaanku.
Namun, saat perhatiannya teralih pada hal lain. Dia tidak menyadari aku menatapnya.
Aku memperhatikannya.
Aku merasa tidak nyaman berada dekatnya, karena ada sesuatu hal yang menarik aku padanya.
Aku ingin mencari tahu apa itu. Cukup positif, jika dibandingkan
dengan aku berusaha menuliskan betapa tidak adil-nya Tuhan padaku...
Dahinya penuh kerutan. Kulitnya kasar. Tak menimbuklkan kesan khusus apapun padaku. Hanya dia seseorang yang terlihat lelah.
'Aku hidup dengan kopi instan.' Katanya tiba-tiba, berbalik
menghadapku dan menatapku langsung. Mendapatiku salah tingkah, ketahuan
menatapnya.
Tapi dia tersenyum. Tidak lagi menggodaku.
'Jadi,' Kataku, 'Kopi instan. Hm...1906 itu tahunnya dan ditemukan G. Washington. Itu yang kubaca.'
'Sayang sekali, aku tidak bisa memberimu segelas kopi instan disini.
Jadi, ini, espresso. Lebih baik, jika kamu sudah menyelesaikan makan
malammu. Mau kubuatkan?'
Dia mengangguk. 'Aku juga mencari orang yang menemaniku makan, sejujurnya...' Dia mencoba lagi.
Aku tertawa.
'Kamu mau?' tanya Glass penuh harap.
'Aku tertawa karena aku mengingat sesuatu.'
Dia bertanya tanya. Namun tidak melanjutkan pertanyaannya. Glass
menikmati menatapku bekerja. Kebanyakan begitu. Mereka yang datang
menatapku, namun mereka memikirkan masalah mereka sendiri.
'Aku tidak sedang di mood yang baik, Glass.'
'Sebaliknya, aku sedang di mood yang paling baik.' Jawabnya. 'Baiklah, coba ceritakan apa yang membuat mood mu bisa lebih baik.'
'Sulit.'
'Coba dan buktikan aku terlalu bodoh untuk mendengar ceritamu.'
'Ini soal favorit. Ini soal apa yang menjadi yang paling kamu sukai.' Jawabku.
Aku melanjutkan dengan asal-asalan,
'Aku suka gelang kaki, tidak ada seseorangpun yang mengetahuinya. Itu yang membuatku kesal...'
'Ayo, kita beli gelang kaki...' senyumnya, aku akan segera menghapal senyumnya. Tidak boleh!!!!, 24 wajah Billy menyelamatkanku.
Aku mengabaikannya.
Larut. Sudah larut malam. Dan Glass mengorder gelas ke 3, dengan
kopi yang berbeda-beda, dan menikmati tiap tegukannya. Tentunya bangga
melihat caranya menikmati kopiku, tapi aku ingin pulang, bersembunyi,
beristirahat.
Glass. Penuh energi. Duduk didepanku, tak ada tanda-tanda ingin pulang. Dia tamu terakhir malam itu.
'Glass, aku ingin pulang. Aku harus tutup coffee shop ini malam ini. Bisakah kamu balik dilain waktu?'
'Aku antar kamu?'
'Tidak, tidak usah.'
Dia beranjak dari kursinya. Membayar dan keluar. Begitu saja.
Meninggalkan perasaan kosong dihatiku, mau tidak mau, itu harus
kuakui, itu yang kurasakan. Aku tidak menyangka dia akan benar benar
beranjak pulang.
Setelah menutup lampu, mengunci pintu, aku berjalan pulang. Ditemani
cahaya lampu yang dramatis disepanjang jalan setapak Pearl City.
Malam.
Aku berharap bisa seberuntung malam-malam sebelumnya, tertidur, tanpa mimpi.
Dan tangan itu menarikku. Aku berteriak.
Namun suaranya menyadarkanku, suara yang kukenal.
'Keira.'
'Glass.'
Dia, lagi.
'Biarkan aku istirahat, Glass.'
'Biarkan aku tahu ceritamu, Kei. Everythings gonna be all right.'
Dan begitu saja, keluar dari mulutku, semua dalam kalimat-kalimat
yang tidak pernah aku susun. Begitu saja. Semua dalam nada datar penuh
kekecewaan. Penuh kemarahan.
Aku tidak peduli dia tidak mengerti, aku bahkan tidak peduli, jika dia mengerti.
Mungkin, aku kehilangan kesabaran. Mungkin dia terlalu baik. Mungkin dia bukan siapa-siapa.
'Tidak ada yang tahu apa yang kusukai. Kamu tahu, aku menyukai
gelang kaki. Butuh sampai bertahun-tahun, nenek baru menyadari apa yang
kusukai.'
'Jadi, jangan bersikap kamu adalah penolong untukku, Glass. Kamu tidak tahu, tidak tahu.'
'Aku tidak butuh. Karena jika aku menyukai sesuatu. Maka itu yang akan diambil dariku.'
'Jika aku menginginkan sesuatu, maka aku orang yang harus merelakan keinginan itu berlalu.'
'Inilah yang terbaik yang bisa aku dapatkan, dan kamu tidak perlu tahu, Glass. Sebab,'
'Bukan kemungkinan.'
'Menganggap Tuhan tidak adil, adalah suatu kesombongan. Aku
meminta ampun untuk kesombonganku, tapi aku masih merasa tidak adil.'
'Walau semua yang tidak pernah aku inginkan, sudah ada dihadapanku
dan berjalan sangat baik. Aku masih memikirkan apa yang aku harapkan,
satu persatu menuntut aku mempertanyakan keadilan itu.'
Wajahku panas. Dan aku mungkin sudah hampir menangis.
'Jadi, tidak. TIDAK. Everythings not gonna be all right.'
Aku berjalan masuk.
'It has to be not all right. So, stand back, and let me rest.'
Dan,
Aku tidak tahu, apakah aku tertidur atau tidak malam itu.
(Luke) 4:10 for it is written, ‘He will command his angels
concerning you, to protect you,’ 4:11 and ‘with their hands they will
lift you up, so that you will not strike your foot against a stone.’”
Coz i knew His answer.